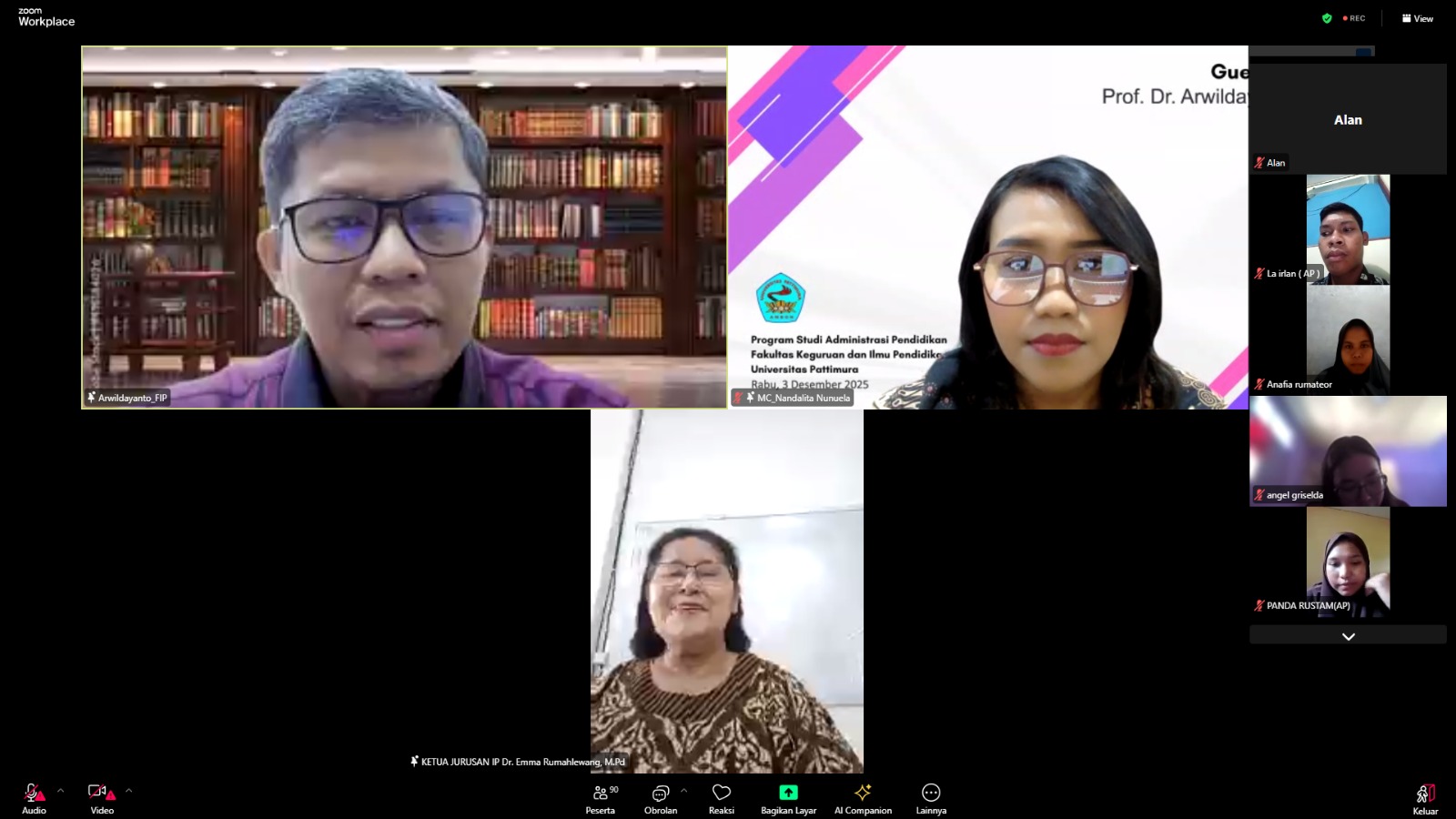fip.ung.ac.id, Gorontalo – Istilah ekspektasi yang dalam Bahasa Inggrisnya “expectation” dengan kata dasar “expect” memiliki arti menyangka atau mengharapkan. Dalam pergaulan sehari-hari sering terdengar ungkapan”jangan berekspektasi berlebihan terhadap saya” atau jangan terlalu berekspektasi tinggi dan sebagainya. Dengan begitu dapat dimaknai, bahwa ekspektasi adalah harapan terhadap sesuatu yang akan ditemui, didapatkan atau diperoleh yang melintas dalam pikiran.
Karena ekspektasi baru sebatas pada bayang-bayang pikiran yang melintas dalam benak seseorang, maka ekspektasi sebenarnya belum memiliki kepastian, masih dalam angan-angan yang terkadang membuat seseorang dihantui oleh rasa penasaran bahkan tidak sabar menunggu untuk membuktikan apakah ekspektasi seseorang terhadap sesuatu itu benar adanya atau tidak.
Oleh karena itu dalam realitas kehidupan sehari-hari, terkadang ekspektasi melahirkan 2 rasa, yakni rasa puas atau rasa kecewa. Puas apabila apa yang ditemuinya, diinginkannya dan dikehendakinya sesuai dengan ekspektasinya sejak awal. Sementara rasa kecewa muncul apabila harapan besarnya, impiannya dan apa yang dibayangkan dan dikehendakinya jauh dari panggang api.
Itulah sebabnya orang-orang bijak sering berujar “jangan terlalu berekspektasi pada sesuatu atau pada seseorang secara berlebihan agar ketika realitas yang ditemui tidak sesuai atau jauh dari ekspektasi kita maka rasa sakit dan kecewa tidak sampai menusuk ke dalam jantung yang paling dalam.
Sebab, kekecewaan atau rasa sakit akibat mendapatkan realitas tidak sesuai ekspektasi akan memunculkan penyakit hati, dendam, benci, iri hati, arogan, angkuh, merasa benar bahkan terkadang banyak yang menjadi hilang ingatan atau gila.
Dari sinilah kemudian banyak para ahli merekomendasikan, agar dalam menggapai harapan, cita-cita dan keinginan tetap bersandar pada realitas yang terukur sesuai dengan kemampuan dan kapasitas diri. Dalam istilah yang lain, sebelum berekspektasi ya..harus “tahu diri” agar ketika ekspektasi itu tidak sesuai dengan kenyataan tidak akan membuat “anda” menjadi sakit hati, benci, dendam dan merasa diri paling benar sehingga menjadi “lupa diri” dengan memaksakan kehendak pada orang lain.
Seburuk-buruknya penyakit yang diderita manusia.adalah merasa paling hebat, paling benar sehingga menjadi angkuh, arogan, menjadi pembenci bagi yang lain apalagi sampai “memaksakan kehendak dengan cara-cara yang seakan sudah di luar nalar dan akal sehat orang lain.
Dalam tataran idealnya, ekspektasi harus tetap merujuk pada kemampuan dan kapasitas diri yang terukur. Jika tidak, maka ekspektasi terhadap sesuatu atau pada seseorang akan menjadi “salah kaprah”.
Bagaimana mengukur diri? Salah satu instrumen yang tersaji dalam nilai-nilai agama, diantaranya, adalah muhasabah, mengenal diri, introspeksi diri, memotret diri sendiri dari berbagai sudut, mulai dari kualitas diri, kapasitas diri hingga menjadi “tahu diri” dari mana ia berasal dan hendak kemana ia harus menuju.
Banyak fenomena dan kejadian yang menjadi contoh dan patut dijadikan sebagai madrasah kehidupan,betapa pentingnya “mengukur diri’ atau “tahu diri” dalam berekspektasi, apalagi berekspektasi tentang hasil yang ingin dicapai. Gangguan mental, kasus gila mendadak, stress dan depresi, adalah deretan kasus yang disebabkan dan bersumber dari ekspektasi yang tidak sesuai kenyataan.
Apalagi dalam menghadapi pesta demokrasi 2024 mendatang saat ini. upaya mengukur diri dan berekspektasi secara wajar menjadi instrumen yang seakan menjadi keharusan. Meski konstitusi negara menjamin dan memberi kebebasan kepada setiap warga negara untuk mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif misalnya, namun dalam ranah personal atau individu, tetap dituntut sikap “mawas diri”, maju bukan karena latah atau sekadar ikut-ikutan, juga bukan sekadar memenuhi keinginan dan hasrat semata, tapi juga berbicara tentang bagaimana “mengukur” kemampuan dan kapasitas diri yang terkadang diplesetkan dengan “3 tas”, yakni integritas, kualitas dan “isi tas”.
Dengan begitu, aspek penting di era demokrasi saat ini yang menganut sistem “proporsional terbuka” adalah “performance personal” bukan semata-mata performance secara kelembagaan. Itulah sebabnya, persoalan nomor urut selama era reformasi semenjak pemilu 2004, tidak lagi menjadi “sumber konflik” seperti yang terjadi pada zaman orde baru misalnya.
Kalaupun saat ini masih ada yang mempersoalkan “nomor urut” pada sistem proporsional terbuka, maka kesan yang muncul adalah “performance personalnya” berarti kurang memadai sehingga mendambakan proporsional tertutup.
Selain “Performance personal”, instrumen penentu lainnya adalah tingkat kepercayaan rakyat dan modal sosial yang cukup. Kesemuanya itu dapat ditelaah melalui upaya “kenal diri” secara jujur dan apa adanya.
Upaya “mengukur diri” dengan demikian, menjadi sangat penting agar ekspektasi terhadap hasil masih tetap dalam koridor yang terukur pula. Dengan begitu, pesta demokrasi benar-benar dapat dimaknai sebagai “pesta” yang identik dengan kegembiraan dan kebersamaan, bukan sebaliknya memunculkan ketegangan, permusuhan bahkan suasana mencekam.